“Polemik tutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Danau Toba kembali mencuat. Ribuan pekerja terancam kehilangan mata pencaharian, sementara kerusakan lingkungan disebut semakin parah. Bagaimana jalan tengahnya?”
Simalungun|Simantab – Seruan agar pemerintah menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) kembali mencuat. Narasi ini tidak hanya datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi adat, tetapi juga dari tokoh keagamaan.
Alasannya, perusahaan yang membutuhkan kayu eucalyptus ini dinilai telah meninggalkan jejak panjang permasalahan lingkungan dan sosial di kawasan Danau Toba.
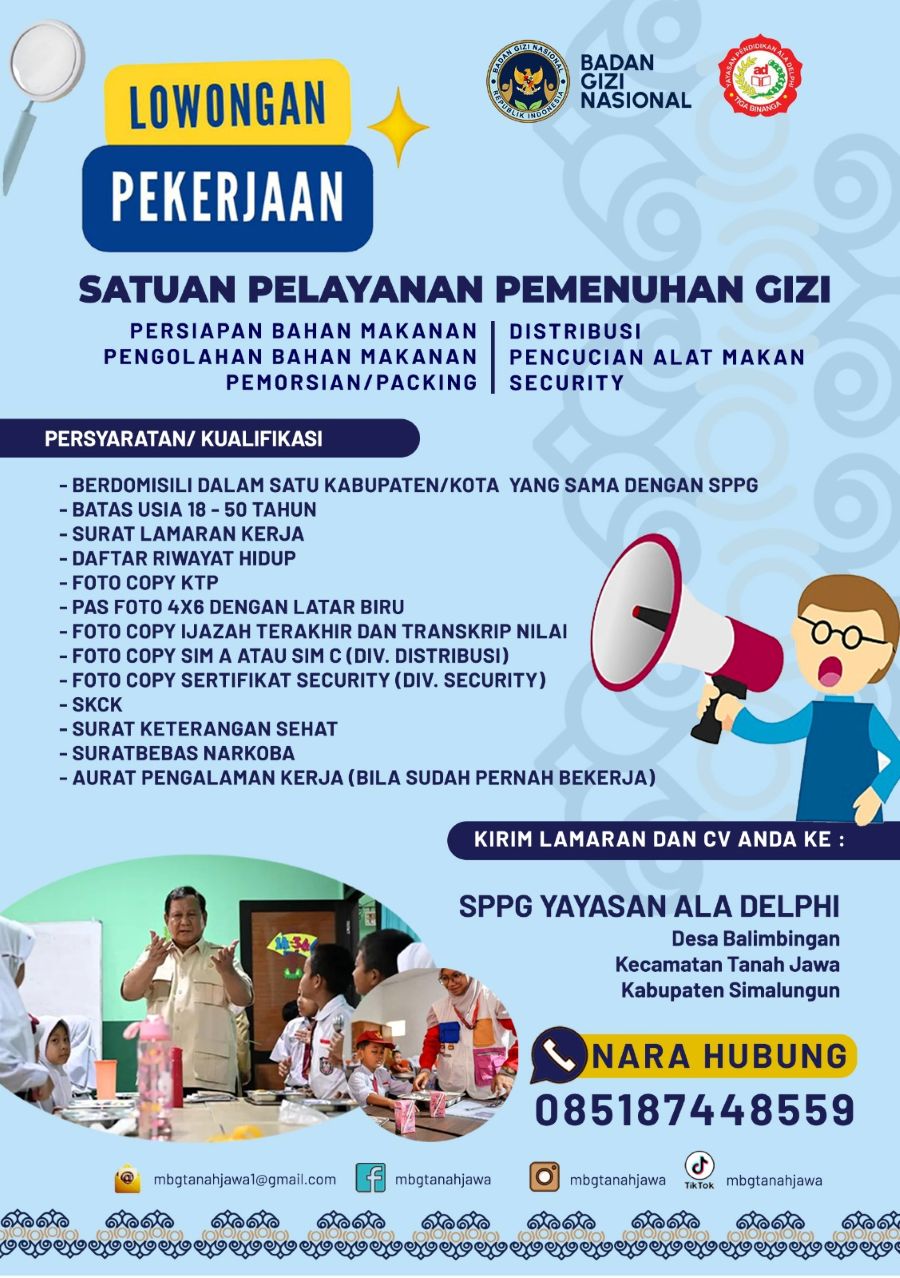
Namun, di balik suara lantang yang meminta penghentian operasi, ada pula cerita lain yang jarang terdengar: suara pekerja dan keluarga yang kehidupannya bergantung pada keberadaan TPL.
Suara Pekerja: Penutupan Akan Menghantam Semua Aspek
Seorang karyawan yang bekerja sejak 2020 sebagai pengawas di Departemen Energi TPL, Jefferson Sitorus, mengaku khawatir dengan tuntutan sepihak untuk menutup perusahaan.
“Seruan tutup TPL ini berdampak ke segala aspek. Tidak hanya kepada ribuan pekerja langsung dan mitra, tapi juga pada keluarga mereka, usaha kecil di sekitar, hingga kehidupan sosial masyarakat luas,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Menurutnya, perdebatan soal lingkungan memang penting, tetapi solusi yang ditawarkan tidak boleh berhenti pada seruan penutupan.
“Kita juga harus jujur, siapa yang siap menggantikan peran TPL dalam menampung tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjaga lahan konsesi yang luasnya ratusan ribu hektare? Kalau lahan itu kosong tanpa pengawasan, justru akan jadi sasaran penebangan liar,” tuturnya.
Jefferson menegaskan bahwa sebagai pekerja, ia tidak menolak adanya evaluasi ketat, audit lingkungan, maupun perbaikan tata kelola perusahaan.
“Silakan dikritik, silakan diaudit. Tapi jangan serta-merta diminta tutup tanpa memikirkan masa depan masyarakat luas. Kita bicara tentang kehidupan puluhan ribu orang, bukan sekadar angka di atas kertas,” katanya.
Warga Kecamatan Girsang Sipanganbolon ini juga berharap, jika wacana penutupan terus digulirkan, pemerintah dan pihak pendukung opsi itu menyiapkan rencana konkret.
“Kalau memang tutup TPL jadi jalan keluar, apa alternatif pekerjaannya? Bagaimana menjamin keberlangsungan ekonomi keluarga kami? Jangan sampai seruan itu hanya jadi jargon, sementara kami di bawah menanggung akibatnya,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar konflik di lapangan, seperti yang pernah pecah di Sihaporas, tidak dijadikan alat provokasi.
“Biarlah penegak hukum yang menindak tegas, supaya masalah tidak terulang di tempat lain,” tambahnya.
Catatan Hitam Sejak 1990
Di sisi lain, Rocky Pasaribu dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) menilai penutupan TPL justru menjadi solusi. Ia menyebut sejak awal beroperasi, perusahaan tidak pernah lepas dari persoalan hukum, baik soal izin, tata kelola lahan, maupun pengabaian hak masyarakat adat.
“Kerusakan ekologis sudah masif. Ada 50 sungai besar dan ribuan anak sungai yang mengalami degradasi. Bahkan kualitas air Danau Toba ikut terancam,” tegas Rocky, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, manfaat ekonomi yang dijanjikan TPL juga minim. Data 2019 menunjukkan perusahaan hanya mempekerjakan 691 karyawan dan 486 mitra kerja.
“Bukan kesejahteraan yang tercipta, justru kerugian ekologis dan sosial yang lebih nyata,” ujarnya.
Perspektif Ekonomi: Antara Investasi dan Risiko Penutupan
Pandangan berbeda datang dari kalangan akademisi. Pengamat ekonomi, Manuntun Parulian Hutagaol, menilai seruan penutupan TPL tidak berdasar pada analisis logis dan data yang jelas.
“TPL adalah investasi besar bernilai triliunan rupiah dengan siklus bisnis jangka panjang. Kalau benar mereka merusak lingkungan, justru mereka sendiri yang rugi. Karena bahan baku kayu tidak bisa tumbuh di tanah yang rusak,” katanya.
Ia menambahkan, penutupan TPL akan berdampak besar pada pengangguran. Diperkirakan terdapat sekitar 13.000 orang bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada keberadaan perusahaan ini.
“Apakah pemerintah siap menampung dan menciptakan lapangan kerja baru bagi mereka? Situasi ekonomi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Manuntun menjelaskan dilema ini meruncing pada satu titik: apa yang lebih besar, kerugian lingkungan atau kerugian sosial-ekonomi?
“Dari sisi pekerja, TPL adalah sumber kehidupan. Dari sisi aktivis lingkungan, TPL adalah biang kerusakan yang harus segera dihentikan,” ungkapnya.
Ia menekankan perlunya analisis biaya-manfaat sosial. Kerugian ekologis seperti kerusakan air, penurunan sektor pariwisata, hingga dampak kesehatan harus ditimbang dengan manfaat ekonomi berupa lapangan kerja, program tanggung jawab sosial, serta stabilitas investasi.
Jalan Tengah Masih Gelap
Seruan penutupan TPL memang menggema, tetapi solusi konkret pasca-penutupan masih samar. Siapa yang akan menjaga lahan bekas konsesi seluas 160 ribu hektare agar tidak menjadi sasaran penebangan liar? Bagaimana memastikan masyarakat yang kehilangan pekerjaan tidak semakin terjerumus ke dalam kemiskinan yang justru bisa memperparah perusakan lingkungan?
Polemik ini masih menggantung. Satu hal yang pasti, masa depan Danau Toba dan masyarakat sekitarnya tidak bisa hanya ditentukan oleh seruan emosional, melainkan harus melalui kajian mendalam yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.(Putra Purba)







